Ada Apa di Secangkir Kopi?

Oleh: Ali Rukman
Pendiri Perhimpunan Kawokh Bungkok Lampung Barat
Setiap kali dunia menyeruput kopi Lampung, mereka hanya mencium harum dan menyanjung cita rasa. Tapi di balik itu, ada pertanyaan yang tak pernah dijawab: ada apa sebenarnya di secangkir kopi itu?
Coba tanyakan pada keluarga Gunarso di Sumber Agung, yang Februari 2024 kehilangan kepala keluarganya diterkam harimau. Atau pada Sahri dari Bumi Hantatai yang di bulan yang sama meregang nyawa dengan cara serupa.
Tanyakan pula pada Karim di Kali Bata Suoh yang September 2024 tak pernah lagi pulang dari kebunnya. Pada Zainudin yang Januari 2025 tubuhnya ditemukan terpotong-potong di hutan Batu Brak. Atau yang baru-baru ini 5 September 2025, selamat dengan luka-luka, setelah harimau menerkamnya di jalan pulang. Mereka semua petani kopi.
Mereka yang menanam, merawat, dan memanen Kopi . Tetapi siapa yang ikut menanggung luka mereka? Tidak ada. Yang ada hanya berita singkat di media, lalu hilang, sementara roda ekspor kopi terus berputar, memenuhi cangkir-cangkir dunia dengan kebanggaan semu.
Harimau dituding sebagai pembunuh, padahal ia juga korban. Rimba yang mestinya rumahnya sudah lama berkurang dicincang jadi kebun. Mangsa alaminya mulai hilang, aliran sungai menyusut, dan akhirnya manusia yang ditemuinya di batas hutan menjadi mangsa pengganti.
Kita menyebutnya konflik, padahal sejatinya ini pembunuhan berantai: hutan dibunuh, harimau dibunuh, dan kini manusia pun ikut jadi korban. Menurut para ahli ekologi satwa liar, Konflik manusia-harimau adalah alarm ekologis.
Jika harimau masuk kampung, itu berarti ekosistem di dalam hutan sudah rusak parah. Tanpa intervensi serius, bukan hanya harimau yang punah, tapi juga manusia di sekitarnya yang kehilangan rasa aman.
Bagi masyarakat Lampung Barat, kopi bukan sekadar tanaman. Ia adalah identitas, warisan, dan nafas kehidupan. Dari kebun kopi, anak-anak bisa bersekolah. Dari kebun kopi, dapur bisa tetap ngebul. Dari kebun kopi pula, hajatan, pesta adat, hingga ibadah bisa berjalan.
Bagi sebagian besar petani di Lampung Barat Kopi adalah penyangga utama ekonomi rumah tangga, bahkan menjadi perekat sosial dalam tradisi gotong royong. Di pasar-pasar kecil Suoh, Sekincau, Belalau,Batu Brak, hingga liwa kopi adalah bahasa sehari-hari: ditimbang, dijual, ditukar dengan kebutuhan lain.
Di ruang-ruang keluarga, kopi adalah cerita yang diwariskan dari leluhur. “Menanam kopi berarti menjaga hidup,” begitu keyakinan yang tak pernah mati di masyarakat tepi Bukit Barisan. Namun di balik makna itu, ada kenyataan getir: untuk mempertahankan kopi sebagai sumber hidup, para petani khususnya mareka yang berkebun di sekitar TNBBS harus menanggung risiko kehilangan nyawa. Dan itu adalah harga yang terlalu mahal untuk sebuah komoditi global yang hanya dilihat dunia dari sisi selogan, aroma, dan rasa.
Lalu di mana para pemilik modal? Di mana para eksportir kopi yang menumpuk laba dari biji yang lahir di tanah yang sama dengan jejak darah ini? Mereka duduk nyaman di kantor berpendingin ruangan, menghitung untung dari setiap kontainer kopi yang berlayar ke luar negeri. Mereka berbicara tentang kualitas, branding, dan pasar global. Tapi satu hal yang mereka tidak pernah mau hitung: nyawa petani yang hilang di rimba.
Ahli kebijakan lingkungan menyebut, “Kopi adalah komoditi global dengan rantai nilai yang panjang. Jika perusahaan hilir hanya bicara sustainability untuk pasar, tanpa berkontribusi nyata pada konflik satwa-manusia di hulu, maka itu hanyalah pencitraan kosong. Rantai pasok harus ikut membiayai solusi di lapangan.”
Inilah ironi paling pahit. Petani kecil di tepi hutan harus berjudi dengan nyawa demi kopi yang jadi komoditi dunia. Sementara perusahaan besar di hilir rantai hanya pandai memoles citra “sustainability” di brosur-brosur pemasaran. Sustainability macam apa, jika di balik secangkir kopi ada darah petani dan raung harimau yang terusir? Saatnya bicara terang-terangan: ini bukan lagi sekadar soal konservasi, melainkan soal keadilan.
Para eksportir, pedagang besar, hingga lembaga keuangan wajib urun rembuk dan urun dana. Mereka harus ikut membiayai mitigasi konflik: sistem peringatan dini, kompensasi keluarga korban, pemulihan habitat, hingga skema perlindungan petani di garis depan. Jangan biarkan beban ini hanya ditanggung oleh petani miskin yang bahkan tak pernah mencicipi secangkir kopi mahal yang mereka hasilkan.
Tetapi solusi sejati tidak akan pernah tumbuh jika hanya digambar di atas kertas proyek. Ia harus lahir dari tanah tempat darah menetes, dari kampung yang tiap malam dihantui raungan hutan. Di situlah kearifan lokal masyarakat Lampung Barat mesti diberi ruang. Sejak lama, leluhur menitipkan falsafah nemui nyimah—menyambut, menjaga harmoni, dan menghormati sesama makhluk.
Dalam adat, hutan bukan sekadar ruang kosong untuk dieksploitasi, melainkan ruang sakral yang menyimpan keseimbangan hidup. Maka, penyelesaian konflik manusia-harimau harus memaksimalkan partisipasi masyarakat: dengan tanda-tanda alam yang mereka kenali lebih dalam dari peta satelit, dengan doa dan ritual adat yang mengingatkan manusia untuk menempatkan harimau sebagai saudara tua dalam kosmos.
Sebab jika petani hanya dijadikan objek kebijakan, solusi akan rapuh. Tetapi jika mereka menjadi subjek—duduk di lingkaran musyawarah, menjaga hutan dengan cara yang diwariskan leluhur—maka jalan keluar akan berakar. Harimau pun tak lagi hanya dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai penanda: bahwa rimba masih hidup, bahwa keseimbangan masih bisa dipulihkan.
Saatnya dunia mendaratkan keadilan dan kemanusiaan di ranah paling nyata: di hulu, di kebun, di tepian rimba tempat petani kopi bertaruh hidup. Jangan biarkan secangkir kopi hanya menjadi simbol gaya hidup global, tetapi abaikan darah dan tangis yang mengiringinya.
Jika tidak, maka setiap teguk kopi dunia adalah teguk darah. Setiap cangkir yang terhidang di kafe-kafe megah itu adalah pengkhianatan terhadap hutan, harimau, dan petani yang jadi tumbal.
Ada apa di secangkir kopi? Jawabannya jelas: ada aroma, ada kenikmatan, tapi juga ada luka, ada tangisan, ada darah. Dan dunia harus tahu itu. (**)
Berikan Reaksi Anda
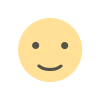
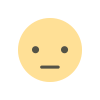

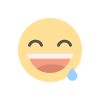

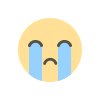
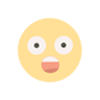













































































:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5248047/original/053653000_1749554445-IMG-20250610-WA0006.jpg)






:strip_icc():format(webp):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1180,20,0)/kly-media-production/medias/5339703/original/049546400_1757086230-20250904AA_Timnas_Indonesia_vs_China_Taipei-25.JPG)



















